Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.102.2
Konten dari Pengguna
Berkembangnya Upaya Konservasi di Indonesia
29 Oktober 2024 21:48 WIB
·
waktu baca 5 menitTulisan dari Akhdiat Dimas Abimanyu tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
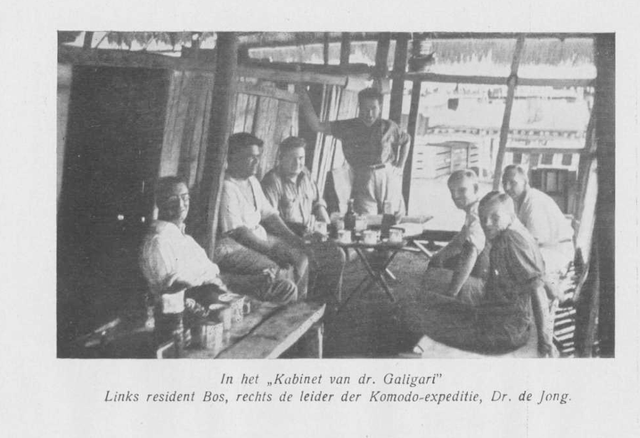
ADVERTISEMENT
Perkembangan upaya konservasi di Indonesia tidak lepas dari pengaruh eksternal yang merambah Nusantara. Pada 252 SM, Raja Ashoka dari Dinasti Maurya di India memulai kebijakan perlindungan terhadap satwa, perikanan, dan hutan, sebuah semangat konservasi yang kemudian mencapai Kerajaan Sriwijaya pada 684 M. Kebijakan ini mencakup pengaturan dan perlindungan kawasan alam di Sumatera yang tampak dalam adat masyarakat yang menjaga dan memistifikasi benda-benda atau tempat tertentu, termasuk larangan mengambil jenis pohon, batu, atau memasuki kawasan hutan, gunung, dan rawa tanpa izin.
ADVERTISEMENT
Bukti konservasi pada masa Majapahit ditemukan dalam Prasasti Malang (1395), yang memuat kebijakan perlindungan terhadap padang alang-alang di Gunung Lejar dari risiko kebakaran. Di samping itu, masyarakat dilarang mengeksploitasi sumber daya hutan dan pantai, seperti menebang kayu atau mengambil telur penyu. Konservasi Majapahit berfokus pada wilayah aliran sungai dan bertujuan menciptakan masyarakat yang peka terhadap kondisi ekologi dan sosial. Pada masa ini juga berkembang aturan lokal terkait fungsi pengelolaan kehutanan, seperti sistem "Wewengkon Desa," yaitu wilayah yang dikelola oleh demang dan rakyat atas izin penguasa, termasuk kawasan hutan. Untuk pengubahan lahan atau pembangunan pemukiman di kawasan ini, izin khusus dari raja atau pejabat yang berwenang sangat diperlukan.
Memasuki era kolonial, kebijakan konservasi mengalami kekosongan selama 188 tahun (1714-1912), seiring dengan dominasi sektor agrikultur yang diperkuat oleh kesuburan tanah dan iklim yang mendukung. Ekspansi agrikultur yang dikelola pemerintah kolonial bertujuan memulihkan ekonomi Hindia Belanda, sementara kontrol terhadap keanekaragaman hayati cukup lemah, sehingga perburuan liar terutama terhadap hewan besar menjadi hal yang umum. Aktivitas perburuan ini diikuti oleh tradisi aristokrat lokal, yang memandang berburu kijang atau rusa sebagai simbol status sosial. Di Priangan, misalnya, lahan perburuan mencapai 12.000 hektare dan mengakibatkan terbunuhnya ratusan kijang hingga kegiatan ini menurun seiring dengan peningkatan populasi Belanda yang menggeser status masyarakat setempat.
ADVERTISEMENT
Perburuan liar yang dilakukan kaum bangsawan lokal berakar pada budaya yang menempatkan satwa liar sebagai objek hiburan, baik melalui perburuan maupun pertarungan antar hewan. Pertarungan antara satwa seperti kerbau dengan harimau, babi dengan domba, dan adu ayam, sering digelar di alun-alun kerajaan, termasuk di Kesultanan Yogyakarta sejak 1791. Pertarungan ini juga dianggap sebagai ritual pengguguran dosa di momen Idul Fitri dan Tahun Baru Hijriyah.
Perubahan pandangan terhadap konservasi dipengaruhi oleh gerakan konservasi di Inggris dan Amerika Serikat. Inggris mengalami peningkatan studi terhadap alam, terutama di koloni-koloninya, sedangkan di Amerika Serikat, Presiden Theodore Roosevelt memperkenalkan nilai konservasi berbasis etika. Gerakan ini menganggap perburuan sebagai tindakan brutal dan menekankan tanggung jawab moral manusia terhadap alam. Di Hindia Belanda, perburuan liar terhadap burung cenderawasih dan mamalia lain mulai ditentang oleh kalangan ilmuwan dan pejabat lokal. F.S.A de Clerq, Residen Ternate pada 1890, melaporkan hampir musnahnya burung cenderawasih di pantai akibat perburuan liar yang berlanjut hingga pedalaman, memicu kekhawatiran akan kepunahan. Sejumlah usulan pelestarian muncul, termasuk dari entomolog M.C. Piepers yang menyarankan pendirian taman konservasi model Yellowstone untuk melindungi spesies terancam punah.
ADVERTISEMENT
Namun, pemerintah kolonial menanggapi permasalahan ini secara lambat. Meski Gubernur Jenderal Jhr. C.H.A van der Wijck pada 1894 meminta laporan terkait perdagangan burung di Ternate dan Ambon, hasilnya minim. Respon lamban ini menimbulkan kritik dari pihak eksternal. Pada 1896, P.J. Van Houten menggunakan media Belanda untuk meningkatkan kesadaran tentang spesies yang terancam, khususnya burung cenderawasih. Tahun 1909, pemerintah kolonial menerbitkan Staatsblad 497 dan Staatsblad 594 untuk membatasi perburuan burung dan mamalia serta meluncurkan Peraturan Perlindungan Mamalia dan Burung pada 1910.
Namun, regulasi ini memiliki kelemahan, karena tidak melindungi spesies yang dianggap berbahaya, sehingga perburuan terhadap harimau, kera, dan kelelawar tetap dilakukan. Selain itu, peraturan ini hanya berlaku di Jawa, bagian selatan Sumatera, dan wilayah kecil lainnya, sehingga sebagian besar daerah pedalaman tetap terbebas dari larangan perburuan. Pada 1912, nilai kulit burung dari Manokwari mencapai satu juta gulden, yang kemudian memicu tekanan lebih keras dari Asosiasi Perlindungan Alam untuk membatasi ekspor burung cenderawasih. Akibatnya, pada 1922, pemerintah kolonial melarang perburuan kasuari dan cenderawasih, meskipun burung cenderawasih kuning tetap dibolehkan.
ADVERTISEMENT
Seiring dengan perburuan liar, penebangan hutan juga meningkat, terutama di kawasan pegunungan, yang mengakibatkan krisis air di daerah lereng gunung seperti Sindoro. Kondisi iklim yang tidak menentu antara tahun 1844 hingga 1850 menyebabkan gagal panen dan kekeringan panjang, yang pada gilirannya mendorong banyak pihak untuk mencari solusi guna menjaga keragaman hayati di Hindia Belanda. Kesadaran akan pentingnya lingkungan kemudian mendorong pembukaan Kebun Raya Cibodas pada tahun 1889 yang semakin dikukuhkan oleh keputusan pemerintah pada tahun 1890. Kesadaran kolonial terhadap pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati juga dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan yang masuk ke Hindia Belanda.
Pemerintah kolonial mulai menyusun regulasi kehutanan pada masa pemerintahan Willem Daendels di awal abad ke-19, tetapi penerapannya tersendat karena kendala politik. Baru pada 1865, Reglemen Hutan pertama diterbitkan, diikuti perubahan pada 1874, 1882, dan Ordonansi Kolonial tahun 1897, hingga munculnya Reglemen 1913. Namun, kebijakan ini tetap kurang efektif mengurangi pembabatan hutan yang meningkat akibat permintaan akan lahan dan permukiman.
ADVERTISEMENT
Kritik terhadap pembabatan hutan terus meningkat, yang mengarah pada pembentukan Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming oleh Sijfert Hendrik Koorders, sebuah organisasi dengan pengaruh besar dalam kebijakan pelestarian hutan. Setelah Perang Dunia I, pemerintah kolonial mengubah pendekatan konservasinya dan memperkuat semangat pelestarian hingga era kemerdekaan Indonesia.
Pada 1932, pemerintah kolonial meluncurkan Ordonansi Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, yang menciptakan kategori "suaka margasatwa" guna mengatasi keterbatasan akses terhadap cagar alam yang terisolir di pedalaman. Kawasan suaka margasatwa yang signifikan didirikan, termasuk Baluran di Jawa seluas 25.000 hektar dan Gunung Leuser serta Way Kambas di Lampung dengan luas total 900.000 hektar, serta Kutai dan Sampit di Kalimantan seluas 650.000 hektar. Upaya ini menandai awal terbentuknya kebijakan konservasi yang terstruktur, yang nantinya berlanjut dan menjadi fondasi bagi kebijakan konservasi di Indonesia merdeka.
ADVERTISEMENT

