Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.94.0
Konten dari Pengguna
Representasi Penindasan Perempuan dalam Budaya Minang melalui Siti Nurbaya
27 Oktober 2024 13:35 WIB
·
waktu baca 5 menitTulisan dari Dimas Aldean Ubaidillah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
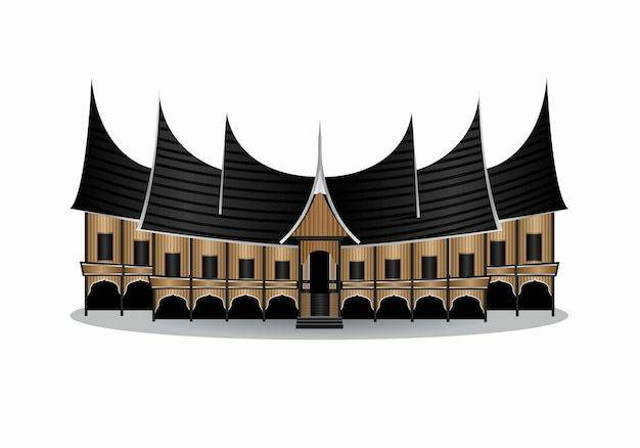
ADVERTISEMENT
Novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah sastra Indonesia. Karya yang diterbitkan pada tahun 1922 ini tidak hanya dikenal sebagai cerita tentang cinta yang tragis, tetapi juga sebagai cerminan kritik sosial terhadap adat istiadat yang berlaku di masyarakat Minangkabau pada masa itu. Dalam novel ini, penindasan terhadap perempuan menjadi tema sentral yang dibingkai dalam budaya patriarki meski Minangkabau dikenal dengan sistem matrilineal.
Di Minangkabau, meskipun garis keturunan ditarik dari pihak ibu, peran perempuan sering kali terpinggirkan dalam keputusan-keputusan besar yang menyangkut kehidupan mereka. Sistem adat yang mengatur kehidupan masyarakat Minangkabau ternyata tetap memberikan kekuasaan dominan kepada laki-laki dalam mengontrol perempuan. Hal ini sangat terlihat dalam nasib yang dialami oleh Siti Nurbaya, yang dijodohkan tanpa persetujuannya dengan Datuk Maringgih, seorang laki-laki tua yang kaya raya.
Siti Nurbaya adalah simbol perempuan yang terjebak dalam tatanan adat yang menekan kebebasan dan hak-haknya. Penindasan yang dialami Siti Nurbaya bermula ketika ayahnya, Baginda Sulaiman, terjerat hutang kepada Datuk Maringgih. Untuk menyelamatkan keluarganya, Siti Nurbaya terpaksa menikah dengan Datuk Maringgih, meskipun ia tidak mencintainya. “Perempuan tidak berdaya di hadapan adat dan uang. Bukan kehendaknya yang menentukan, melainkan adat yang kaku,” tulis Marah Rusli dalam menggambarkan situasi ini.
Melalui karakter Siti Nurbaya, Marah Rusli menunjukkan bahwa perempuan di Minangkabau berada di bawah kendali adat yang memberikan otoritas kepada laki-laki dalam pengambilan keputusan penting. Siti tidak punya pilihan selain mematuhi keputusan ayahnya. Dalam salah satu kutipan, Siti Nurbaya berkata, “Bukan kemauan hamba yang hidup di bawah kekuasaan ayah dan adat, tapi takdir yang menghantarkan.”
Penindasan yang dialami oleh perempuan dalam novel ini tidak hanya terbatas pada Siti Nurbaya. Beberapa karakter perempuan lain juga menghadapi situasi serupa. Misalnya, karakter Fatimah, istri kedua Datuk Maringgih, juga dipaksa menikah untuk memenuhi keinginan orang tuanya. Meskipun dalam sistem matrilineal, perempuan memiliki hak atas harta pusaka, hak mereka untuk memilih pasangan hidup atau menentukan jalan hidup sering kali ditentukan oleh keluarga dan adat.
Melalui penggambaran ini, Marah Rusli ingin menunjukkan bahwa sistem matrilineal yang dipandang menguntungkan perempuan ternyata tidak menjamin kebebasan mereka dalam hal-hal yang lebih personal seperti cinta dan pernikahan. Sebaliknya, sistem tersebut justru memperkuat kontrol sosial terhadap mereka. Dalam budaya Minang pada masa itu, pernikahan sering kali dilihat sebagai alat untuk memperkuat ikatan sosial dan ekonomi, sehingga perasaan dan keinginan pribadi perempuan kerap diabaikan.
Dalam novel ini, Datuk Maringgih menjadi simbol kekuatan patriarki yang menindas perempuan. Ia menggunakan kekayaannya untuk memaksa Siti Nurbaya menikah dengannya, meskipun ia tahu bahwa Siti mencintai Samsulbahri. “Dengan uang, adat bisa tunduk, dan perempuan tak lagi punya suara,” demikian salah satu kutipan yang mempertegas dominasi kekuasaan ekonomi atas hak perempuan. Datuk Maringgih memandang perempuan hanya sebagai barang yang bisa dibeli dan dimiliki, tanpa memperhitungkan perasaan atau kehendak mereka.
Kisah cinta Siti Nurbaya dan Samsulbahri adalah perlawanan terhadap adat yang menindas. Keduanya saling mencintai, tetapi cinta mereka tidak bisa bersatu karena tekanan sosial dan adat yang begitu kuat. Bagi Siti Nurbaya, cintanya kepada Samsulbahri adalah bentuk kebebasan yang ia impikan, namun realitas kehidupan menghalanginya untuk mencapai kebahagiaan itu. “Cinta adalah angan yang tak bisa dipeluk oleh tangan yang terbelenggu adat,” ujar Siti Nurbaya dalam salah satu dialognya.
Meskipun Siti Nurbaya akhirnya meninggal karena racun yang diberikan oleh suruhan Datuk Maringgih, kematiannya menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan. Ia lebih memilih mati daripada harus terus hidup dalam penderitaan akibat pernikahan yang dipaksakan. Marah Rusli seolah ingin menunjukkan bahwa meskipun perempuan berada dalam posisi yang lemah di hadapan adat, mereka tetap memiliki kekuatan untuk melawan, meski dengan cara yang tragis.
Novel Siti Nurbaya juga memperlihatkan bagaimana peran laki-laki dalam penindasan ini tidak hanya terbatas pada tokoh seperti Datuk Maringgih. Ayah Siti Nurbaya, Baginda Sulaiman, meskipun tidak sekejam Datuk Maringgih, juga berperan dalam mengekang kebebasan putrinya. Ia memaksakan pernikahan Siti demi kepentingan finansial, meskipun ia tahu bahwa putrinya tidak bahagia. Dalam kutipan lain, Siti Nurbaya mengungkapkan kesedihannya, “Ayahku, yang seharusnya melindungi, malah menjeratku dalam kurungan yang dibuatnya sendiri.”
Tidak hanya Siti, banyak perempuan dalam masyarakat Minang pada masa itu yang mengalami nasib serupa. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit antara menjalankan adat atau memperjuangkan kebebasan diri. Kehidupan perempuan diatur oleh aturan yang mengutamakan kehormatan keluarga dan stabilitas sosial, bukan kebahagiaan individu. Marah Rusli menggambarkan hal ini dengan sangat gamblang dalam dialog-dialog para tokohnya.
Namun, meskipun Siti Nurbaya merupakan kritik terhadap adat Minangkabau, novel ini tidak sepenuhnya menolak adat tersebut. Sebaliknya, Marah Rusli mengajukan pertanyaan penting tentang bagaimana adat bisa beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya. Novel ini mengisyaratkan bahwa adat seharusnya tidak menjadi alat penindasan, tetapi harus mampu berkembang agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu, terutama perempuan.
Samsulbahri, sebagai tokoh laki-laki yang mencintai Siti Nurbaya, juga menjadi simbol perubahan. Ia mewakili generasi muda yang menolak ketidakadilan dan penindasan. Meskipun akhirnya ia tidak bisa menyelamatkan Siti Nurbaya, perannya menunjukkan bahwa tidak semua laki-laki dalam budaya Minangkabau setuju dengan adat yang menindas perempuan. “Bukan adat yang harus dihormati, melainkan manusia dan perasaannya,” kata Samsulbahri dalam salah satu adegannya.
Novel ini juga mengajak pembaca untuk berpikir ulang tentang peran perempuan dalam masyarakat. Apakah perempuan hanya menjadi objek yang harus tunduk pada adat dan kehendak laki-laki, atau mereka bisa menjadi subjek yang menentukan nasibnya sendiri? Melalui Siti Nurbaya, Marah Rusli menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, meskipun jalan tersebut sering kali penuh dengan rintangan.
Kesimpulannya, Siti Nurbaya adalah karya yang menyuarakan penindasan yang dialami perempuan dalam bingkai adat dan budaya Minangkabau. Meskipun sistem matrilineal memberikan posisi sosial tertentu bagi perempuan, kenyataannya mereka tetap tidak bebas dalam menentukan nasibnya sendiri, terutama dalam hal pernikahan. Melalui cerita Siti Nurbaya, Marah Rusli mengajak kita untuk merenungkan kembali adat yang tidak selalu berpihak kepada kemanusiaan, serta pentingnya reformasi sosial agar perempuan bisa mendapatkan kebebasan dan keadilan yang layak.
Kritik Marah Rusli terhadap adat dalam novel ini tetap relevan hingga hari ini. Penindasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk masih terjadi di berbagai lapisan masyarakat, baik melalui sistem sosial, adat, maupun agama. Siti Nurbaya mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk kesetaraan gender masih harus terus dilakukan, baik dalam konteks lokal maupun global.
ADVERTISEMENT

