Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Konten dari Pengguna
Dinamika Partai Islam di Sumbar
10 Maret 2024 11:04 WIB
·
waktu baca 7 menitTulisan dari Israr Iskandar tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
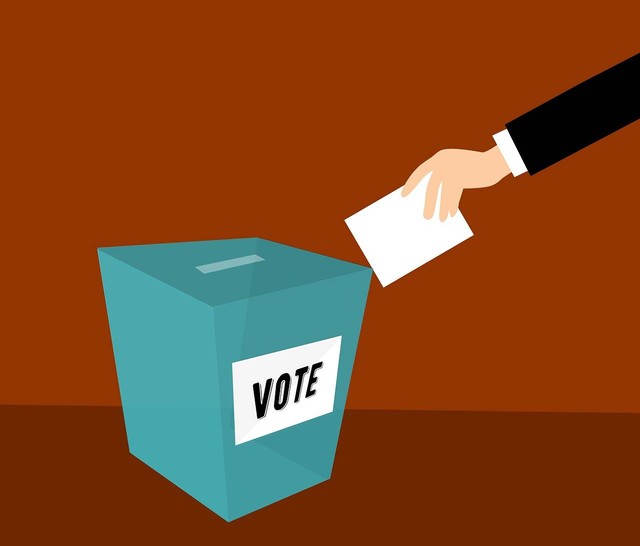
ADVERTISEMENT
Pemilihan Umum Tahun 2024 tetap akan menjadi tanda tanya bagi partai-partai Islam, termasuk di Sumatera Barat sekalipun. Di daerah yang dikenal sebagai basis utama partai-partai Islam di masa lalu itu, suara kumulatif partai-partai religius tetap kalah dibandingkan suara partai-partai nasionalis.
ADVERTISEMENT
Jika merujuk data quick count (hitung cepat) beberapa lembaga survei, peta hasil pemilu legislatif di Sumatera Barat menunjukkan adanya persaingan setidaknya lima partai: PKS, Gerindra, Golkar, Nasdem dan PAN. Namun dari lima besar itu, hanya PKS yang secara harfiah merupakan partai Islam, selebihnya adalah partai-partai nasionalis.
Padahal, dalam catatan sejarah, partai Islam di masa lalu pernah berjaya di Sumatera Barat. Pada Pemilu 1955, partai Islam Masyumi tampil sebagai jawara di daerah ini dengan perolehan suara sekitar 49 persen, diikuti Perti pada angka sekitar 28 persen suara. Partai Islam lainnya berukuran lebih kecil, seperti NU (0,7 persen). Kumpulan suara semua partai Islam tersebut mencapai angka sekitar 80 persen (Amal, 1982: 57).
ADVERTISEMENT
Bandingkan dengan partai-partai non-religius. PKI, misalnya, memang seolah menjadi partai non-agama terbesar di ranah Minang di dekade itu, tetapi suaranya hanya 6,5 persen saja. Sementara PNI yang menjadi pemuncak di tingkat nasional, di Sumatera Barat hanya mendapatkan suara 0,7 persen saja. Partai yang didirikan Sukarno di masa pergerakan nasional itu kurang populer di kalangan orang Minangkabau (Amal, 1982: 57).
Ketika pecah pemberontakan PRRI pada akhir 1950-an, eksistensi partai-partai politik yang punya basis kuat di Sumatera Barat, khususnya yang beridiologi Islamis, menjadi sangat terganggu. Bubarnya Masyumi pada tahun 1960, karena tokoh-tokoh top-nya terlibat dalam pergolakan daerah, praktis membuat mayoritas urang awak kehilangan saluran politiknya. Perti memang masih eksis, tetapi partai ini pada masa pasca-PRRI tidak bisa dianggap mewakili aspirasi mayoritas warga daerah. Alih-alih berharap, Perti malah menjadi bagian dari sistem otoritarian. Bersama PNI, PKI, NU dan sejumlah partai lain, Perti menjadi bagian dari model bangunan kekuasaan “Nasakom” (nasionalisme, agama dan komunis).
ADVERTISEMENT
Pada masa “Demokrasi Terpimpin” praktis tidak ada pemilu, walaupun partai-partai tetap eksis. Secara statistik, tidak bisa diukur partai mana yang unggul dan paling berpengaruh pada zaman itu. Sekalipun demikian, apabila mencermati perkembangan di lapangan, kekuatan politik pada masa ini bertumpu pada tiga elemen utama yang mungkin hampir sama kuat pengaruhnya: Soekarno, Angkatan Darat dan PKI (Feith, 1995). Pada konteks itu jelas bahwa secara kepartaian PKI lah yang paling berpengaruh. Tidak heran para analis mengatakan jika pemilu digelar pada awal 1960-an itu, niscaya partai kiri dengan corak aspirasi revolusioner itu akan tampil sebagai pemenang, suatu keadaan yang tidak diinginkan sejumlah golongan non-komunis, terutama Angkatan Darat dan sekutu luar negerinya.
Keadaan berubah ketika rezim Demokrasi Terpimpin tumbang menyusul kegagalan kudeta PKI di awal Oktober 1965. Tragisnya, perubahan politik saat itu bahkan juga ditandai serangkaian bencana kemanusiaan di berbagai daerah, termasuk Sumatera Barat. Pada konteks itu, Angkatan Darat tampil sebagai aktor utama transformasi politik. Tentara bahkan secara perlahan dan pasti kemudian bergerak ke panggung kekuasaan dengan dukungan golongan Islam dan kaum intelektual, termasuk mahasiswa. Pada momen-momen itulah Orde Lama secara gradual berganti menjadi Orde Baru.
ADVERTISEMENT
Di Sumatera Barat, tragedi 1965 juga berdampak pada situasi politik lokal. Bahkan rakyat di daerah ini merespon tragedi nasional di “malam jahanam” itu dengan mendukung upaya penumpasan PKI dan melikuidasi Orde Lama. Kelompok-kelompok pergerakan Islam, terutama dari kalangan muda, seperti HMI, PII, dan PMII, bahkan sejak Oktober 1965 dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya tampil di garda depan tidak hanya dalam upaya menggusur kekuatan rezim Sukarno di daerah tetapi juga mendukung penuh tampilnya Orde Baru Soeharto.
Ketika aliansi pembentuk dan pendukung Orde Baru benar-benar sudah sepenuhnya tampil di singgasana kekuasaannya, pemilu sebagai basis legitimasi politik pun dilaksanakan. Pemilu dimaksud akhirnya digelar pada 3 Juli 1971. Pemilu kedua dalam sejarah Indonesia itu menjadi sangat penting bagi Jenderal Soeharto dan rezim Orde Baru secara keseluruhan, yakni sebagai basis legitimasi, terutama di mata dunia internasional. Soeharto sangat membutuhkan dukungan internasional untuk program-program modernisasi yang dilancarkannya sejak sebelum Pemilu.
ADVERTISEMENT
Pesta demokrasi 1971 tersebut sudah berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pemilu 1971 bahkan hanya dianggap sebagai pseudo democracy alias “demokrasi abal-abal”. Sebab perangkat kekuasaan yang muncul dan menguat sejak pergantian politik pada pertengahan dekade sebelumnya telah merekayasa Pemilu untuk memenangkan kontestan pendukung pemerintah, yang dalam konteks ini diwakili oleh (Sekber) Golkar (Golongan Karya).
Pada saat itu, kekuatan-kekuatan politik lama dibatasi dan dikebiri. Unsur kekuatan nasionalis dan Islam, yang menjadi dua poros kekuatan politik model lama, tidak banyak berkutik. Bayangkan, dua partai yang masing-masing menjadi “ahli waris” dua kekuatan politik terbesar di tahun 1950-an, tidak mendapatkan suara yang signifikan pada Pemilu 1971. PNI yang menjadi pemenang pada pemilu 1955 hanya memperoleh 6,93 persen suara, sementara Parmusi yang notabene memiliki “tali darah” dengan Masyumi, partai Islam terbesar di masa lalu, hanya memperoleh 5,36 persen suara.
Hanya NU yang konsisten bahkan naik sedikit, sehingga mendapatkan suara sebanyak 18,6 persen, tetapi secara politik juga tak banyak berpengaruh vis a vis kekuatan politik pemerintah yang dalam pemilu diwakili Sekber Golkar. Apalagi di luar hasil Pemilu yang dikontestasikan di tempat-tempat pemungutan suara di seluruh pelosok negara, kekuatan pro-pemerintah bertambah gemuk dengan adanya jatah kursi legislatif dalam jumlah yang banyak untuk militer dan polisi.
ADVERTISEMENT
Di Sumatera Barat, Pemilu 1971, dalam batas tertentu, tidak hanya mencerminkan perubahan situasi politik nasional, tetapi juga lokal. Golkar sebagai kendaraan pemerintah menang besar di daerah ini, bahkan persentasenya melebihi perolehan suara Beringin secara nasional. Selain sebagai akibat politik “buldozer” pemerintah, kemenangan Golkar dan keterpurukan partai non-Beringin di daerah ini juga sebagai akibat trauma politik masa lalu yang dialami rakyat Minang. Trauma politik PRRI dan tekanan politik pada masa pra-Orde Baru seolah telah menjadi dasar bagi elit dan rakyat Sumatera Barat untuk menempuh jalan pragmatis yakni dengan memilih Golkar dan meminggirkan partai Islam, sebagai saluran politik masa lalu mereka.
Sikap pragmatis, bahkan hiper-pragmatis, semacam itu berlanjut pada pemilu-pemilu Orde Baru berikutnya. Orang Minang lebih memilih ikut “kapal besar” dibandingkan “kapal kecil”. Tidak heran Golkar sebagai catch all party selalu menang besar. Puncaknya kejayaan Golkar adalah pada Pemilu 1997, atau pemilu terakhir Orde Baru, di mana Beringin berjaya di angka 91,5 persen suara di seluruh Sumatera Barat. Di tingkat nasional, partai yang corak politiknya menafikan model politik aliran dan memanfaatkan “massa mengambang” itu meraup 84 persen suara.
ADVERTISEMENT
Bandingkan dengan suara PPP, yang merupakan hasil fusi partai-partai Islam, ternyata suaranya anjlok ke dasar sejarah Orde Baru. Padahal logikanya, PPP mestinya bisa menang besar di negeri yang adat dan budaya masyarakatnya bersendikan pada ajaran Islam, seperti terangkum dalam aforisme adat bersendi syarak syarak bersendi Kitabullah. Sebagai partai yang merupakan kombinasi partai Islam modernis dan Islam tradsionalis, serta kekuatan Islam lain, suara PPP seharusnya bisa mencapai 80 persen lebih, atau setara dengan kumulasi Masyumi, Perti, NU dan PSII di masa Demokrasi Liberal. Namun kenyataannya, pada Pemilu 1997, suara PPP di Sumatera Barat hanya 7,74 persen saja, sebagai pencapaian terendah partai Islam dalam sejarah politik sejak Indonesia merdeka.
Peta politik kemudian berubah seiring jatuhnya rezim Orde Baru, berganti dengan Orde Reformasi. Termasuk di Sumatera Barat. Tadinya muncul spekulasi bahwa model spektrum politik lama kembali muncul di jagat politik Indonesia pasca Soeharto, khususnya pada pelaksanaan Pemilu 1999 dan terutama pada pemilu-pemilu selanjutnya.
ADVERTISEMENT
Namun faktanya bercerita lain. Alih-alih menguatnya kompetisi politik kepartaian berdasarkan ideologi lama, yang muncul dan menguat kemudian adalah persaingan berdasarkan pola-pola politik pragmatis, bahkan hiper-pragmatis, di kalangan pelaku politik. Partai-partai dan elit politik seperti kehilangan “ruh” perjuangannya. Orang kemudian sulit membedakan partai religius dan partai nasionalis (sekuler). Pada konteks itulah bisa dipahami, mengapa pamor partai-partai Islam secara umum terus menurun dari pemilu ke pemilu, termasuk di Sumatera Barat.

