Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.101.0
Konten dari Pengguna
'Orang Tua dan Laut' dan Wajah Kebudayaan Amerika
18 Januari 2017 9:33 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:19 WIB
Tulisan dari NARASASTRA tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT

Sudah selayaknya sebuah negara memiliki wajah yang berbeda-beda dalam sejarah. Kita mengenal Amerika Serikat sebagai negara adidaya setelah ia masuk pada blok yang menang Perang Dunia dan unggul pada perang teknologi menuju 1970.
ADVERTISEMENT
Lantas bagaimana wajah kebudayaannya?
Lesunya ekonomi mereka saat itu mengharuskan banyak orang kehilangan pekerjaan dan banyak usaha menengah di kota-kota besar harus ditutup karena kesulitan melangsungkan kerja.
Kecenderungan nilai yang diangkat oleh para seniman dan penulis saat itu berusaha mengkritik pemerintahan pusat yang dinilai tidak mampu melindungi ekonomi masyarakat.
The Great Depression mempertaruhkan hidup banyak orang saat itu, dan saat nilai tukar saham serta ekonomi pusat dianggap mengganggu kehidupan ekonomi banyak orang di seluruh Amerika, kekuatan ekonomi di masing-masing negara bagian menjadi jalan untuk memperbaikinya.
ADVERTISEMENT
William Faulkner, Walter Prescott Webb, dan Lewis Mumford adalah para budayawan dan penulis yang berusaha menggaungkan nilai-nilai regionalisme saat ekonomi sentral di Amerika waktu itu dianggap bobrok.
Para budayawan mengkritik pemerintahan pusat dan para pengarang berusaha melihat kehidupan kecil para masyarakat Amerika di pedesaan. Faulkner, misalnya, menggambarkan kehidupan masyarakat Amerika dengan gaya narasi monolog interior yang khas dalam Light in August dan As I Lay Dying.
Pada periode awal abad ke-20 ini, penulis Amerika--dan yang nanti disebut sebagai penulis terbaik di Dunia--Ernest Hemingway lahir.
ADVERTISEMENT

Melihat tahun aktif Hemingway pada pertengahan abad ke-20, ia seakan tak memiliki tempat di kesusastraan Amerika saat masa The Great Depression dan southern literature.
Kehidupan pribadinya ketika ia ikut pada Perang Dunia sebagai supir ambulans memberi tempat dan pengalaman penting bagi dirinya. Ia menjelajah Eropa pada masa-masa perang dan karya-karyanya yang kuat seperti A Farewell To Arms dan For Whom The Bell Tolls.
Di antara sekian karyanya, Orang Tua dan Laut sering dianggap karya terbaik yang membuatnya mendapatkan Pullitzer setahun setelah karya itu diterbitkan dan juga membuatnya mendapat Hadiah Nobel.
ADVERTISEMENT
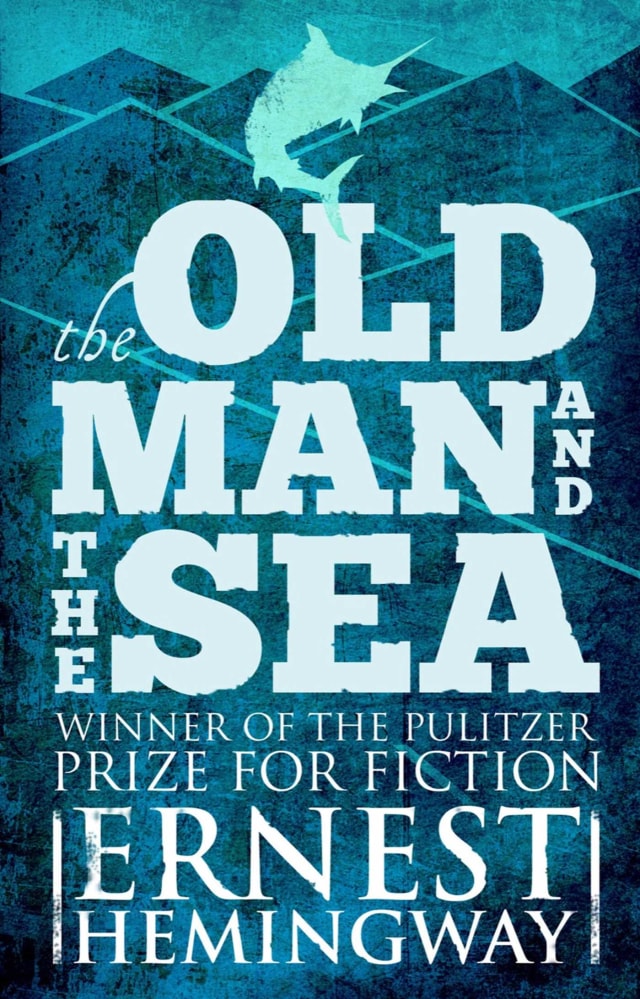
Karya itu lahir setelah dua dekade kelumpuhan ekonomi yang kritis menerjang Amerika dan pengalaman Perang Dunia.
Di mana kekuatannya?
Hemingway pernah berpendapat bahwa ia mengharapkan Karen Blixen yang justru memenangkan hadiah Nobel tahun itu untuk sebuah memoar tentang Afrika yang menurutnya lebih kontekstual dibanding karya-karyanya.
Ia menganggap Orang Tua dan Laut yang saat itu digandrungi terlalu sederhana untuk mendapatkan hadiah-hadiah ini.
Orang Tua dan Laut adalah cerita singkat tentang seorang nelayan.

Pada awal cerita, Santiago sang nelayan diceritakan masih bersahabat dengan mantan anak buah kapalnya, seorang bocah yang menaruh perhatian penuh pada Santiago.
Si Bocah diharuskan meninggalkan Santiago oleh orang tuanya karena Santiago dianggap sudah seharusnya tidak lagi melaut karena terlalu tua. Si Bocah amat mengagumi Santiago karena Santiago banyak mengajarkan ilmu melaut dan memancing.
ADVERTISEMENT
Keduanya menghadirkan hubungan yang dekat dan memberikan banyak nilai tentang umur serta perjuangan. Metafora dan analogi yang kuat dapat dilihat dari kutipannya yang berikut:
“Mengapa lelaki tua bangun sangat awal? Apakah supaya bisa menikmati satu hari lebih lama lagi?”
“Aku tidak tahu,” Kata si Bocah menjawab. “Yang Aku tahu adalah anak muda tidur larut, itupun dengan susah payah.”
Santiago adalah sosok nelayan tua yang masih gigih untuk bisa melaut dan menaklukan ikan-ikan besar.
Hemingway menggambarkannya dengan liris. Ia tinggal di sebuah gubuk di desa nelayan yang kumuh. Ia menggambarkan Santiago memiliki mata yang masih bersemangat. Mata yang telah puluhan tahun menjelajahi samudera. Mata yang belum juga tua.
ADVERTISEMENT
Kisah sederhana ini hanya berputar pada Santiago dan kapalnya yang diceritakan bertemu seekor ikan marlin yang sangat besar pada petualangannya di kisah itu.
Hemingway menggambarkannya dengan sangat detil, persis seperti Herman Melville menggambarkan petualangan Pequod pada Moby Dick.
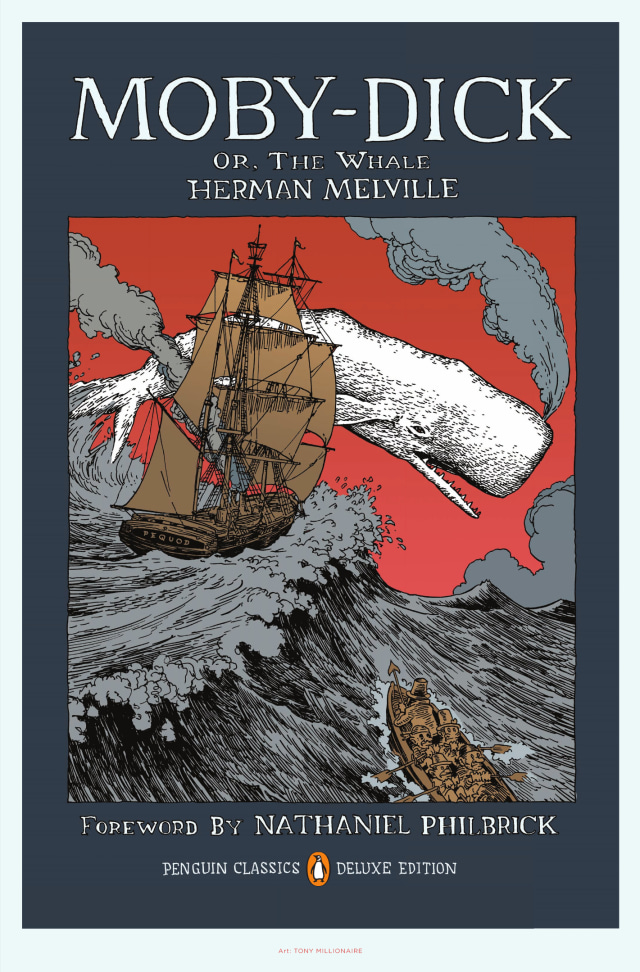
Ia menggambarkan kurun waktu dan kejadian Santiago di atas kapal pada pengarungannya dengan hati-hati. Mulai dari Santiago yang mengingat beberapa fragmen kehidupannya di atas kapal, hingga nantinya menemukan koneksi dengan ikan marlin yang sangat besar itu saat talinya tertarik.
Hemingway menggambarkannya dengan sangat hati-hati dan penuh tekanan. Untuk selanjutnya, di sinilah perjuangan Santiago menaklukan ikan marlin besar itu.
ADVERTISEMENT
Pada akhir cerita, Santiago berhasil menaklukkan ikan marlin itu hanya untuk beberapa saat. Ia tak bisa menaruhnya ke dalam kapalnya yang kecil dan hanya bisa menyeretnya di sisi kapal.
Di sinilah tekanan lain muncul saat ikan hiu yang justru menggerogoti daging ikan marlin yang Santiago tangkap. Santiago sampai ke pantai hanya untuk membawa tulang ikan yang tak bernilai.
Kita akan mendapati Santiago yang tua yang telah ditinggalkan oleh anak buah kapal yang terasa seperti anak sendiri baginya, berhasil menaklukan ikan marlin besar hanya untuk digerogoti ikan hiu.
Pada detik-detik menuju akhir cerita, Hemingway menggambarkan sesuatu yang menarik:
ADVERTISEMENT
“Apa itu?” ia bertanya pada seorang pelayan dan menunjuk tulang punggung panjang dari ikan raksasa yang sekarang telah menjadi sampah menunggu tersapu keluar oleh air pasang.
“Tiburón,” Pelayan itu menjawab. “Hiu.” Ia bermaksud menjelaskan kejadiannya.
“Aku tak tahu ada hiu segagah ini dengan ekor yang dibentuk dengan indah.”
“Aku juga tidak,” teman prianya menimpali.
Ia menyimpul kesalahpahaman dari orang awam yang berusaha melihat tulang-tulang ikan Santiago sebelum pada akhir kalimat dalam cerita disebutkan:
Di atas jalan, dalam gubuknya, lelaki tua itu tertidur lagi. Ia masih tertidur di atas wajahnya dan si Bocah duduk di dekatnya mengawasi lelaki tua itu bermimpi tentang singa-singa.
ADVERTISEMENT
Yang kita tahu, Santiago bermimpi tentang singa-singa yang pernah ia lihat di Afrika saat Santiago masih muda. Kita mungkin hanya tahu bahwa Santiago mendambakan suatu waktu saat ia merasa kuat dan mampu. Saat Santiago masih kuat seperti hewan liar dengan hatinya yang gigih.
ADVERTISEMENT
Apa yang seharusnya dapat disimpulkan dari Orang Tua dan Laut yang ditulis tahun 1952?
Jika melihat kurun waktu dan tempat, mari kita ingat kelumpuhan ekonomi dan depresi di Amerika serta luka perang menuju tahun 1950. Waktu-waktu itu adalah waktu yang penting untuk kembali mendefinisikan kembali kemanusiaan.
Terlepas dari isu besar tentang kelesuan ekonomi negara atau isu Perang Dunia, kita harus kembali pada orang-orang terdekat kita seperti Santiago yang mendamba si Bocah saat ia di atas kapal. Kita harus mempertanyakan kembali, bagaimana hubungan kita dengan alam?
ADVERTISEMENT
Orang Tua dan Laut merenungkan nilai yang sederhana. Meski dianggap tidak kontekstual pada zamannya, Hemingway ingin berusaha memberikan kisah yang merenungkan nilai lain saat kita memikirkan isu yang lebih besar.
Apakah kita bisa sekuat Santiago? Apakah hubungan kita dengan dunia luar dapat sehebat hubungan Santiago dengan laut?
Nilai-nilai penting yang ingin digaungkan tak berangkat pada isu besar seperti kehidupan bersama dan kemiskinan. Ia berusaha mencari nilai-nilai lain. Semangat kebaruan dan perenungan nilai-nilai lain menjadi warisan penting setelah Ernest Heingway dan Orang Tua dan Laut.
ADVERTISEMENT
______________________________________________________________________________________________
Ditya Nurhakiki Subagja, born Bandung 24th July 1994. Currently studying Indonesian Linguistic and Literature at Universitas Indonesia. Former editor in chief for Majalah Gaung at Faculty of Humanities, Universitas Indonesia. Some of his poems are published in Jarak Menghidupkan Hasrat, a collective poetry of Teater Pagupon members. Currently developing Ultra Stardust, Bandung-based publishing house and press with his several friends.

