Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.100.8
Konten dari Pengguna
Literasi di Era AI: Ketika Robot Bisa Bertutur dan Manusia Harus Lebih Bijak
3 April 2025 12:43 WIB
·
waktu baca 7 menitTulisan dari FX Risang Baskara tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Pernahkah Anda tertegun saat membaca sebuah teks dan bertanya-tanya: Apakah teks ini ditulis oleh manusia atau mesin? Saya baru saja melakukannya pagi ini. Membaca artikel tentang tes literasi UTBK SNBT 2025 yang menjelaskan tentang kemampuan "menggali dan mengungkapkan informasi", "memadukan dan menafsirkan makna", serta "menganalisis dan mengevaluasi", saya tergelitik oleh ironi yang menggantung di udara: kita sedang menguji kemampuan literasi sementara ChatGPT dan Claude sudah mampu melewati ujian tersebut dengan nilai sempurna.
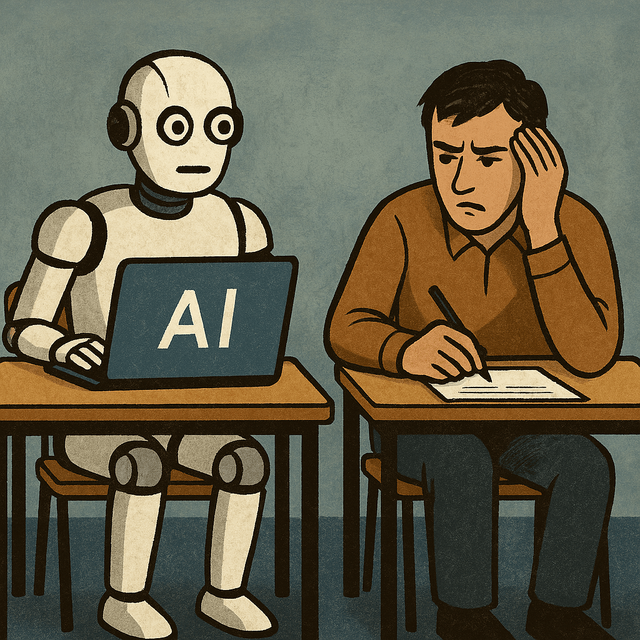
Tes literasi dalam UTBK didesain untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan berinteraksi dengan teks. Kompetensi yang dianggap esensial bagi seorang mahasiswa. Namun bayangkan, di sebelah seorang siswa yang berkeringat menghadapi soal-soal itu, sebuah AI dengan santai mengetik jawaban sempurna dalam hitungan detik.
ADVERTISEMENT
Pertanyaannya bukan lagi "siapa yang lebih pintar?" melainkan "apa artinya menjadi literate di zaman ketika mesin bisa menulis esai, menganalisis puisi, dan bahkan merangkum buku?"
Ketika Menteri Pendidikan kita berbicara tentang "transformasi digital pendidikan" dan menggelontorkan triliunan rupiah untuk "literasi digital," yang sering terlewatkan adalah refleksi fundamental: apakah konsep literasi itu sendiri perlu kita definisikan ulang?
Mari kita renungkan sejenak—apa gunanya mengajarkan siswa menentukan gagasan utama teks atau mengidentifikasi hubungan sebab-akibat jika semua itu sudah bisa dilakukan oleh ChatGPT? Apakah sistem pendidikan kita sedang mempersiapkan siswa untuk berkompetisi dengan mesin pada bidang di mana mesin sudah menjadi juaranya?
Ini bukan sikap teknofobia, tetapi undangan untuk berpikir lebih dalam. Ketika Ujian Tulis Berbasis Komputer masih menguji kemampuan yang sama seperti dekade lalu sementara teknologi telah melompat jauh ke depan, kita perlu mempertanyakan: untuk siapa pendidikan ini dirancang? Untuk dunia di masa lalu, atau di masa depan?
ADVERTISEMENT
Fenomena AI generatif seperti ChatGPT, Gemini, dan Claude telah menghadirkan disrupsi yang mendalam. Para guru di Jakarta Selatan mungkin sudah familier dengan rupa-rupa essay yang dicurigai hasil AI, sementara di pelosok Sumba, siswa masih berjuang dengan akses internet yang tersendat. Ini bukan sekadar kesenjangan digital, tetapi kesenjangan dalam paradigma pembelajaran.
Saat "Copy-Paste" Berevolusi Menjadi "Prompt-Generate"
Dulu, guru-guru kita cemas dengan praktik "copy-paste" dari internet. Sekarang, kekhawatiran telah berevolusi menjadi "prompt-generate", siswa mengetik beberapa kata kunci, dan voila, sebuah esai lengkap dengan struktur rapi dan referensi muncul dalam hitungan detik.
"Pak, kalau semua bisa dibuatkan oleh AI, untuk apa kita masih belajar menulis?" tanya seorang mahasiswa dalam kelas saya sesaat sebelum libur Idul Fitri kemarin. Pertanyaan tersebut bukanlah pertanda kemalasan, melainkan kegundahan eksistensial yang valid. Ketika alat-alat digital menawarkan jalan pintas yang begitu menggoda, bagaimana kita mempertahankan nilai intrinsik dari proses belajar yang penuh perjuangan?
ADVERTISEMENT
Ironinya, di saat sistem pendidikan kita masih berkutat dengan tes literasi konvensional, dunia kerja sudah bergerak jauh melampaui itu. Perusahaan-perusahaan tidak lagi mencari lulusan yang bisa menemukan "inti bacaan" atau "menentukan tema teks", mereka mencari individu yang mampu berkolaborasi dengan AI, memberikan prompts cerdas, mengevaluasi output AI dengan kritis, dan menggunakan teknologi sebagai pemampu, bukan pengganti.
Seorang mahasiswa saya di kelas saya pernah membagikan pengalamannya menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan tugas pembuatan podcast kelompoknya: "Saya minta AI membuat outline, lalu saya bangun argumentasi sendiri berdasarkan outline itu." Adaptasi semacam ini, seperti mendelegasikan tugas-tugas mekanis pada AI sambil mempertahankan otonomi kreatif, mungkin merupakan sedikit dari gambaran dari masa depan literasi yang lebih relevan.
ADVERTISEMENT
Literasi Baru: Kemampuan Membaca Output AI
Definisi literasi yang kita anut selama ini sepertinya perlu diperluas. Di era AI generatif, literasi bukan hanya tentang kemampuan memahami teks, tapi juga "membaca" output AI secara kritis. Ketika Tes Literasi UTBK masih berfokus pada "menentukan kelengkapan paparan kekhasan objek bahasan," para siswa sebenarnya membutuhkan kemampuan untuk:
1. Mendeteksi bias dan asumsi dalam output AI
2. Mengidentifikasi informasi yang potentially misleading
3. Membedakan antara fakta dan AI hallucination
4. Mengevaluasi keterbatasan respons AI
5. Menggunakan AI sebagai kolaborator, bukan pemberi solusi
Literasi di era AI bukanlah tentang menyerah pada mesin, tapi tentang mengembangkan kapasitas meta-kognitif yang lebih tinggi. Ini bukan tentang "manusia vs. AI," melainkan "manusia dengan AI vs. manusia tanpa AI."
ADVERTISEMENT
Pertanyaannya kemudian: apakah sistem pendidikan kita siap beradaptasi? Ataukah kita akan terus mengejar paradigma lama, bagai menggapai bulan dengan tangan?
Pemangkas Anggaran dan Pemoles Retorika
Sementara kita berdiskusi tentang literasi di era AI Generatif, kita tak bisa mengabaikan realitas pahit di lapangan. Kementerian Pendidikan memangkas anggaran pendidikan Rp22,3 triliun, tetapi di saat yang sama menggaungkan retorika tentang "pendidikan digital" dan "literasi AI." Para pejabat dengan bangga mengunjungi sekolah-sekolah elite untuk workshop AI, sementara ribuan sekolah di pelosok masih berjuang dengan masalah listrik dan koneksi internet.
Ini bukan sekadar ketimpangan akses, tapi ketimpangan visi tentang masa depan. Ketika kita berbicara tentang "literasi AI" tanpa memastikan infrastruktur digital yang merata, kita sebenarnya sedang memperlebar jurang antara yang berprivilese dan yang terpinggirkan. Kesenjangan ini bukanlah sekadar tantangan teknis, tapi juga etis. Bagaimana kita bisa berbicara tentang "transformasi digital" ketika transformasi dasar saja belum tuntas?
ADVERTISEMENT
Humanisme Digital: Jalan Tengah yang Terjal
Apakah ini berarti kita harus menolak AI dan kembali ke metode konvensional? Tentu tidak. Sikap defensif semacam itu hanya akan membuat kita semakin tertinggal. Yang kita butuhkan adalah pendekatan yang lebih holistik, sebuah humanisme digital yang menempatkan teknologi sebagai alat untuk memperkuat, bukan menggantikan, kapasitas manusiawi kita.
Bagaimana bentuknya? Berikut beberapa kemungkinan:
Pertama, kurikulum nasional perlu direvisi untuk memasukkan kompetensi "bermitra dengan AI" sebagai keterampilan inti, bukan sekadar add-on semata. Ini bukan tentang mengajarkan siswa cara menggunakan ChatGPT atau alat-alat serupa, tapi tentang membangun pola pikir yang memungkinkan mereka berkolaborasi secara efektif dengan teknologi sambil mempertahankan agency mereka.
Kedua, sistem evaluasi kita perlu berevolusi. Ketika AI bisa menghasilkan esai sempurna, mungkin sudah saatnya kita bergeser dari penilaian berbasis produk (hasil akhir) ke penilaian berbasis proses (bagaimana siswa sampai pada hasil tersebut). Ini memerlukan perubahan fundamental dalam cara kita menyelenggarakan ujian, termasuk UTBK.
ADVERTISEMENT
Ketiga, literasi kritis terhadap AI harus menjadi bagian dari pelatihan guru. Para pendidik perlu dibekali bukan hanya dengan keterampilan teknis untuk menggunakan AI, tapi juga dengan pemahaman mendalam tentang implikasi etis, sosial, dan pedagogis dari teknologi tersebut.
Keempat, kita perlu memastikan bahwa pengembangan literasi AI tidak memperlebar kesenjangan yang sudah ada. Ini berarti investasi serius dalam infrastruktur digital di daerah terpencil, bukan sekadar proyek percontohan di sekolah-sekolah elite.
Dan yang paling penting, kita perlu melibatkan siswa sendiri dalam diskusi ini. Generasi Z dan Alpha, yang tumbuh bersama teknologi ini, memiliki perspektif unik yang sering diabaikan dalam perumusan kebijakan pendidikan. Mereka bukan hanya objek dari transformasi digital, tapi juga subjek yang aktif memaknainya. Kebijaksanaan sederhana ini mungkin lebih berharga daripada segala jargon yang diproduksi oleh konsultan pendidikan berbiaya mahal.
ADVERTISEMENT
Bukan Lagi Menjadi Sekadar "Asal Digital"
Pendidikan di era AI membutuhkan lebih dari sekadar digitalisasi prosedur lama. Bukan sekadar mengganti kertas ujian dengan layar komputer, atau buku teks dengan PDF. Yang kita butuhkan adalah imajinasi kembali secara lebih mendasar tentang apa artinya menjadi literate di zaman ketika literasi konvensional sudah bisa diautomasi.
Ketika Tes Literasi UTBK 2025 masih mengukur kemampuan siswa untuk "menentukan unsur sebab-akibat bacaan eksplanatif," dunia sudah bergerak ke arah di mana AI generatif tidak hanya bisa mengidentifikasi hubungan kausal, tapi juga membuat simulasi kompleks dari berbagai skenario. Kesenjangan antara apa yang kita uji dan apa yang sebenarnya relevan semakin lebar setiap harinya.
Pada akhirnya, literasi di era AI bukanlah tentang kompetisi antara manusia dan mesin. Ini tentang menemukan kembali apa artinya menjadi manusia di tengah laju teknologi yang tak terbendung. Tentang memelihara kapasitas-kapasitas yang memang unik dan tak terlepas dari aspek-aspek manusiawi, seperti rasa bertanggung jawab, empati, kebijaksanaan kontekstual, penilaian etis, sembari memanfaatkan kekuatan AI untuk memperkuat, bukan mengikis, kapasitas-kapasitas tersebut.
ADVERTISEMENT
Jika kita gagal melakukan ini, kita berisiko menciptakan generasi yang secara teknis terliterasi tetapi secara eksistensial tersesat, mampu mengoperasikan teknologi paling canggih tetapi kehilangan arah tentang untuk apa teknologi tersebut digunakan.
Masa depan pendidikan Indonesia di era AI bukan tentang seberapa canggih teknologi yang kita adopsi, tetapi tentang seberapa bijak kita memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan kemanusiaan yang lebih luas. Dan untuk itu, kita memerlukan lebih dari sekadar literasi digital; kita memerlukan apa yang nantinya kita sebut sebagai kebijaksanaan digital.
Salam Cerdas dan Humanis.

